The Process of Dealing With Grief — A Man Called Otto (2022)
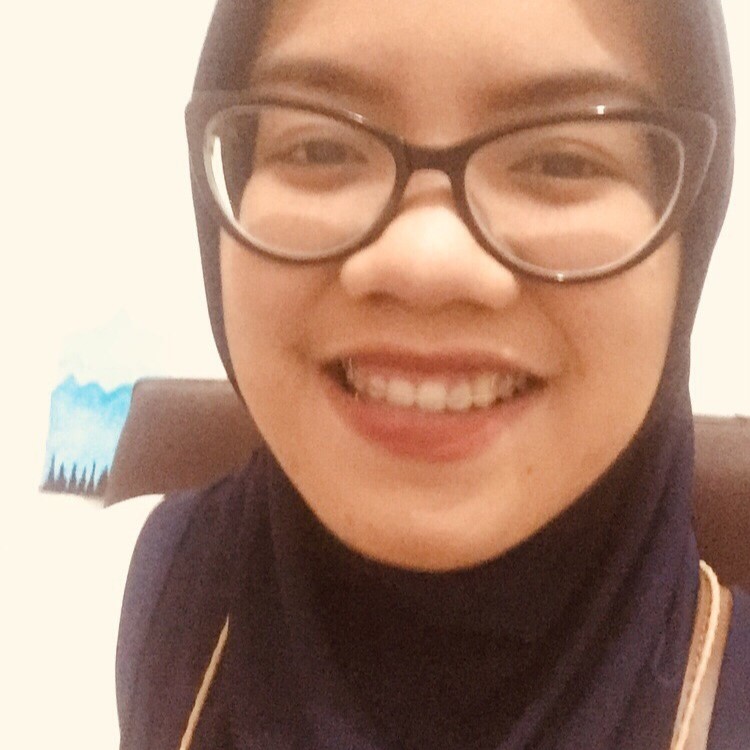 Written by naznienfevrianne on
Written by naznienfevrianne on

Kalau ditanya genre film favorit gue apa… ya, yang kayak gini-gini, nih. Heartwarming, found-family, and stuff. I always eat that every damn time. I’m a sucker for that. Yah, sebenarnya udah terbaca sih dari film-film apa yang gue bicarakan disini. 😁
A Man Called Otto sendiri rilis pada akhir Desember secara terbatas dan rilis internasional pada bulan Januari (termasuk di Indonesia), dan… entah kenapa terbatas banget layarnya disini. Untungnya ada salah satu bioskop yang gak jauh-jauh banget dari rumah gue yang nayangin cukup lama. Jadi, gue masih sempat nonton langsung di bioskop.
Sebelum nonton, gue gak banyak research tentang apa film ini, sih. Review-reviewnya memang banyak seliweran di timeline Twitter, tapi gak gue baca dengan teliti juga. Tau ini film heartwarming dan yang main adalah Tom Hanks, gue memutuskan bahwa gue harus nonton (iya, karena gue SESUKA ITU sama Forrest Gump 😁). Gue juga gak nonton trailer. Sengaja. Emang gue seringnya gitu, sih. Hehehe. Gak tau kenapa, awalnya. Tapi akhir-akhir ini gue sadar bahwa pengalaman nonton film gue terbaik (waktu nonton The Shawshank Redemption pertama kali, lebih tepatnya) adalah saat gue gak tau menahu tentang apa film yang gue tonton. Iya. Kayaknya gara-gara itu gue jadi membiasakan hal tersebut.
Oh. Tapi gue baca summary satu kalimat yang ada di TIX ID, kok. Itu juga karena gue secara berkala ngecekin jadwal tayang filmnya. Other than that, I know nothing. Gue bahkan gak baca buku dan film originalnya—A Man Called Ove—yang seinget gue jadi perwakilan Swedia di Oscars 2017 itu. Ya… gue akui, gue memang belum sebanyak itu nonton film Eropa sih. Film Prancis dan Italia aja gak banyak, apalagi film Swedia.
Film ini dibuka dengan adegan Otto—typical Karen tapi versi bapak-bapaknya gitulah—yang lagi beli tali tambang di salah satu toko material. Pokoknya si Otto ini marah-marah mulu, lah. Lo tau kan tipikal orangtua yang ada apa dikit langsung protes panggil manager? Nah, persis. Otto kurleb orang yang kayak gitu.
Menurut gue ini gak spoiler dan sering disebut-sebut di sinopsisnya, bahwa Otto, adalah tipikal grumpy American dad yang sudah menyerah pada kehidupan. And yes…, the rope that he bought is for… you know. Dan, belum selesai melancarkan aksinya, tiba-tiba ada orang berisik banget di seberang rumahnya lagi repot parkir paralel. Orang tersebut adalah Tommy dan Marisol (di novel aslinya namanya Parvaneh), dengan kedua anak perempuan mereka. Sejak itu, keluarga muda ini sering banget ngerecokin kehidupan Otto yang tinggal sendirian di seberang rumah mereka.
Kekuatan di film ini tentunya ada di hubungan antara Otto dan Marisol. Otto yang grumpy dan kolot banget harus sering-sering ketemu sama Marisol—ibu muda asal Mexico yang cerewet dan suka ikut campur itu. Oh, wow. Unexpected friendship is INDEED my favorite trope!. Mariana Treviño sebagai Marisol IS STEALING ANY SPOTLIGHT. Karakter ini risky banget untuk dibawakan sebenarnya. Kalau pendekatannya kurang tepat, Marisol bisa jadi karakter yang nyebelin banget. Tapi, ya … enggak. Interaksi Marisol dan Otto disini sangat menarik dan kocak. Timing comedy-nya pas dan gak trying to hard. Gak susah lah untuk suka sama hubungan mereka berdua.

David Magee (Life of Pi) sebagai penulis naskah juga banyak menggunakan flashback untuk menjelaskan latar belakang Otto, seperti film originalnya. Penggunaan flashback-nya juga cukup jelas.
American Remakes
Gue sejujurnya gak pernah suka sama remake-remake Hollywood. Kayak … why they need to remake everything?
Tapi, nyatanya gue tidak se-sinical itu sama A Man Called Otto, sih. Ya… I have to admit bahwa A Man Called Otto bukanlah Hollywood remakes yang begitu menyebalkan. Penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan pas. Gak over dan tepat guna. Waktu tau bahwa film ini adalah remake dari film Swedia, gue agak gak membayangkan bagaimana mengadaptasinya. Film Eropa menurut gue cenderung minimalis dan realis. Dan ya… A Man Called Otto tidak menyebrang begitu jauh dari A Man Called Ove, namun terasa mainstream dan pop seperti film Amerika lainnya.
Anyway, setelah selesai menonton A Man Called Otto, gue mencoba untuk menonton A Man Called Ove demi menulis ini. Hahaha. Niat, ya. Perbedaan yang begitu mentereng sih waktu di flashback-flashback itu, ya. Kalau di Otto, flashback-nya lebih fokus ke istrinya, sementara di Ove, flashback-nya itu lebih kompleks, mulai dari Ove masih kecil, membahas juga mengenai bapaknya Ove, hubungan mereka dan inner child-nya si Ove itu sendiri. Menurut gue di Ove memang terasa lebih deep, keputusan Ove mengakhiri hidupnya terasa lebih filosofis. Namun, approach di Otto juga gak salah sama sekali sih. Approach di Otto ini menurut gue akan lebih mudah dimengerti dan lebih relate terhadap penonton umum. This forever soulmate thing is everyone favorite, right?. Di Otto benar-benar digambarkan bahwa istrinya adalah orang terpenting di kehidupan Otto, dimana hidupnya Otto sebelum ketemu istrinya tuh benar-benar hitam putih (Ove literally said that), serta hidupnya lebih bermakna setelah bertemu dengan istrinya. Dan setelah istrinya meninggal dan dia diberhentikan dari pekerjaannya, dia langsung merasa gak punya purpose untuk hidup. Dan ini hal yang mungkin relatable juga buat banyak orang dan sama sekali bukan modifikasi yang salah menurut gue. Otto disini lebih meng-highlight how a certain someone (in this case, of course, is Otto) dealing with grief.

Apalagi ya perbedaan lainnya? Mungkin di karakter Otto dan Ove itu sendiri, ya. Gue gak tau apakah ini karena gue ngefans dengan Tom Hanks atau enggak, tapi Otto sendiri terlihat lebih approachable dan sedikit lebih warm dibanding Ove yang diperankan oleh Rolf Lassgård itu. Ove tuh diem aja udah bikin kita males deket-deket atau membuka pembicaraan. Sementara Otto di mata gue tuh lebih kayak orang grumpy aja yang emang darisananya pembawaannya begitu. Yah… ini agak subjektif sih. But at least that’s what I think about them. Mind my two cents. Hahaha.
Some nitpicks
Selain sukses mematahkan sentimen gue terhadap hollywood remakes, A Man Called Otto adalah film yang hangat dan punya dinamika karakter yang menarik, sampai-sampai kurang lebih dua jam waktu yang gue habiskan untuk menonton film ini gak kerasa sama sekali. Filmnya sendiri agak cukup lama, tapi ternyata durasi tersebut gak menganggu gue sama sekali karena gue udah terlanjur jatuh cinta sama Otto, keluarga Marisol dan tetangga-tetangga lainnya. Ya, bisa dibilang gue betahlah nonton mereka lama-lama. Tapi… apakah ada yang gue tidak suka? Mungkin spesifiknya gak ada ya, but I just prefer the Ove one. Hehehe. Selain itu sih, go run to the cinema and catch it!
Favorite scene
Spoiler alert! Hehehe. Waktu Otto ngajarin Marisol nyetir mobil, sih. Marisol panik banget disitu. Otto ini kan orangnya emang suka goblok-goblokin semua orang ya, kayak bagi dia semua orang selain dia tuh stupid, gitu. Tapi disini Otto mencoba meyakinkan Marisol, kalau Marisol yang imigran, harus belajar bahasa dan budaya baru karena tinggal di negara orang, udah melahirkan dua anak, terus punya suami yang rada-rada bego tapi tetep bisa menjalankan dan melewati hidupnya dengan baik itu harusnya gak perlu pusing perkara masalah sepele, yaitu belajar nyetir mobil. Nyetir mobil adalah hal yang paling gampang setelah berbagai masalah hidup yang Marisol udah lewati. AAAAAA agak gak nyangka soalnya di awal Otto setengah hati banget ngajarinnya dan gregetan sendiri sama Marisol. I tearing up a bit tapi sambil ketawa waktu scene itu. Agak orgil. Tapi biarlah. What a beautifully written scene!

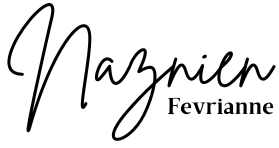



Comments